HARIMAU SUMATERA HEWAN BERADAT VI (98A)

Sejak mengetahui tak lama lagi aku akan berangkat ke Pekanbaru melanjutkan pendidikan, banyak sekali pesan dan wasiat yang disampaikan oleh para sesepuhku. Seakan-akan Pekanbaru itu sangat jauh. Padahal masih wilayah jajaran pulau Sumatera.
“Kau akan tinggal dengan siapa di sana nanti, Dek? Hati-hati. Ingat lain lubuk lain ikannya, lain padang lain pula belalangnya. Pandai-pandailah membawa diri” Pesan Nenek Kam. Perempuan bertubuh ringkih ini nampak semakin tua. Entah mengapa aku jadi sedih menatapnya. Pikiranku jadi sangat jauh merantau ke mana-mana. Ada kekhawatiran jika aku jauh. Bagaimana jika tiba-tiba mendapat kabar Nenek Kam meninggal, atau Kekek Haji Majani, atau Kakek Haji Yasir? Dadaku terasa bergetar. Aku tak sanggup membayangkan kehilangan tiga sosok itu.
Diam-diam kuperhatikan nenek Kam yang tengah menatap kosong jauh ke depan. Mata kecilnya nampak makin hilang di balik kelopak matanya yang sudah turun. Rambutnya yang putih menyembul dari kerudungnya yang longgar, meriap-riap ditiup angin pebukitan. Aku seperti baru menyadari jika lengannya sudah semakin kurus. Urat-uratnya nampak jelas menonjol dibungkus kulit yang keriput. “Nek” Aku berbisik dari jauh. Nenek Kam seperti terperanjat. Beliau langsung menoleh lalu tersenyum menepis perasaannya yang galau.
Beberapa tampuk bunga kopi sudah mulai kering. Bahkan sebagian besar sudah memunculkan putik. Aroma bunga kopi berubah menjadi sedikit pekat bercampur aroma lembab. Calon-calon buah kopi saat ini, menjadi harapan dan impian para petani untuk musim panen tahun depan. Seperti biasa aku akan melihat sinar mata bahagia kakek Haji Yasir tiap kali beliau menatap ‘cap kopi’ atau bakal putik yang akan berubah jadi buah.
Seekor belalang gambir yang bertubuh besar, terbang dan jatuh di hadapanku. Beberapa kali dia berusaha mengepakkan sayap namun gagal. Rupanya dia terbang terlalu jauh, sehingga jatuh di hadapanku. Sayapnya cidera. Samar-samar aku mendengar tangisnya. Meski dia tidak mengucapkan minta tolong, namun dari suara lirihnya menandakan dia butuh pertolongan.
“Sayapmu patah?” Bisikku. Aku hanya mendapat jawaban dari gerakan mata dan antenanya yang juga patah. Akhirnya kupungut belalang gambir yang berukuran besar itu. Kuletakkan di telapak tanganku. Rupanya dia belalang dewasa, sedang mencari lembar daun untuk bertelur. Pelan-pelan kutiup tubuhnya sembari membaca mantra warisan leluhurku. Seketika, suara lirih kesakitannya berubah menjadi ucapan terimakasih. Aku mengangguk pelan sembari menatap titik bola matanya yang mengecil. Tak lama sayapnya mulai mengembang, lalu mengepak cepat hinggap di pohon dedap yang sedang berbunga.
“Dek, lihatlah ke sana” Nenek Kam menunjuk ke salah satu bukit yang melingkar di dusunku. Aku langsung melepar pandang ke arah yang beliau tunjuk. Bukit yang berdiri kokoh, di bawahnya terbentuk sawah luas dan datar. Di bawah jajaran bukit itu dulu ada sawah Bapak dan Ibu, tempat pertama kali aku melihat para nenek gunung yang menyeruapai ‘kerbai’ membantu menanam padi di sawah Bapak.
“Iya, ada apa dengan Bukit Mutung itu Nenek?” Ujarku penasaran. Sebab menurutku tidak ada yang menarik di sana kecuali hutan perbukitan yang sudah berubah menjadi kebun kopi. Beberapa atap pondok nampak memantulkan cahaya ketika tertimpa matahari. Sebentar lagi bukit itu akan terlihat berkabut, karena memang selain tempatnya tinggi, curah hujan makin sering turun di dusunku.
“Kau tahu, mengapa bukit itu disebut Bukit Mutung?” Lanjut Nenek Kam lagi. Aku menggeleng tidak paham. Memang aku belum pernah mendengar mengapa bukit itu dinamakan bukit Mutung. Semula dalam benakku mengatakan pasti bukit itu dulu pernah terbakar atau mutung akibat ulah manusia yang hendak membuka hutan, atau karena ada yang nakal tanpa sengaja membuat hutan itu terbakar atau mutung. Aku memang belum pernah menanyakan pada siapa pun perihal adal mula nama bukit Mutung itu.
“Bukit itu, erat hubungannya dengan cerita Puyang Jagad Besemah. Cerita orang zaman dulu, para moyang kita, di bukit itu Puyang Rie Tabing membuka lahan perkebunan untuk adik perempuannya. Maksud puyang Rie Tabing membukakam kebun untuk adik perempuannya itu, karena suami adiknya seringkali pergi merantau. Sehingga adik perempuannya berusaha sendiri untuk menyambung hidup. Melihat adik perempuannya mencari makan sendiri dengan cara bekerja di kebun atau sawah orang lain, membuat Puyang Rie Tabing ibah. Akhirnya dibuatkannyalah kebun untuk adik kesayangannya. Ketika suami adiknya pulang, beliau mengetahui kalau Puyang Rie Tabing membuatkan istrinya kebun. Dia naik pitam dan merasa tersinggung. Menganggap Puyang Rie Tabing meremehkannya. Padahal, Puyang Rie Tabing melakukan itu karena teramat sayang dengan adiknya” Ujar Nenek Kam.
“Apakah adik ipar Puyang Rie Tabing itu bernama Puyang Serunting Sakti, Nek?” Tanyaku penasaran. Sebab, beberapa kali aku berjumpa dengan leluhurku, ada satu orang yang kulihat pandangannya sedikit liar, lebih banyak bergerak, berjalan-jalan ke sana ke mari daripada duduk diam bercengkrama seperti puyang-puyang lainnya.
“Betul. Adik ipar Rie Tabing itu Puyang Serunting Sakti. Puyang Serunting Sakti ini suka berkelana meninggalkan istri dan kampung halamannya dalam waktu lama, bahkan berpindah-pindah dari dusun satu ke dusun lainnya. Makanya Rie Tabing merasa kasihan dengan adiknya. Agar adiknya punya penghasilan sendiri dibuatkanyalah kebun. Namun sayang, sebelum kebun yang dibuat Rie Tabing selesai, Puyang Serunting Sakti pulang. Mengetahui hal itu beliau marah, merasa kelelakiannya diremehkan. Puyang Serunting Sakti tidak terima.
Pertikaian pun tidak bisa dihindari. Rie Tabing dan Serunting Sakti sama-sama memiliki ilmu yang tinggi. Karena marah, akhirnya Rie Tabing melemparkan segenggam tanah ke arah hutan. Dalam sekejap, hutan yang siap untuk lahan perkebunan itu berubah seperti lautan api. Puyang Serunting Sakti kaget, dia tidak menyangka kakak iparnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Berulang kali Puyang Serunting Sakti hendak mematikannya, namun tidak berhasil hingga sebagian bukit itu terbakar.” Ujar Nenek Kam lagi.
Aku mendengarkan cerita nenek Kam dengan seksama. Dalam batin aku bertanya-tanya, mengapa kedua Puyang itu selalu bertengkar? Padahal mereka dua saudara, kakak dan adik ipar?
Puyang Rie Tabing itu orangnya sangat sabar meski dia tahu adik iparnya itu memiliki sifat dengki padanya. Bahkan, kebun dan ladang mereka yang bersisihan, selalu digeser Puyang Serunting Sakti. Apakah Rie Tabing marah mengetahui tanahnya selalu digeser. Tidak! Padahal kebun adik iparnya itu tidak digarap-garap, dibiarkannya menjadi belukar. Demi melihat kebun Rie Tabing bersih dan subur, dibujuknyalah istrinya agar istrinya minta tukaran kebun pada pada kakaknya.
Apalagi dia mengetahui di kebun kakak iparnya Rie Tabing, selalu ditumbuhi cendawan emas. Muncul keinginannya untuk memiliki kebun itu. Karena Rie Tabing sangat sayang dengan adik perempuannya, diberikannyalah kebunnya pada adiknya. Kebun milik Rie Tabing itu memang aneh. Selain selalu terlihat bersih hal yang membuat Puyang Serunting Sakti iri adalah selalu tumbuh cendawan emas.
Setelah tukaran kebun, mulailah Puyang Rie Tabing menggarap kebun adiknya yang belukar itu hingga bersih seperti kebun yang diberikannya pada adiknya dulu. Sementara kebun adiknya karena tidak pernah digarap oleh Puyang Serunting, berubah menjadi semak belukar. Beliau selalu berkelana tak tahu kemana. Setelah pulang dari berkelana, diketahuinya lagi kalau kebun yang dipelihara Rie Tabing ditumbuhi cendawan emas. Muncullah niatnya lewat untuk kembali menukar kebun. Puyang Serunting Sakti membujuk istrinya untuk tukaran kebun kembali.
Demi adiknya, puyang Rie Tabing kembali mengalah. Diberikannya kebun yang sudah bersih itu pada adiknya. Sementara yang semak belukar kembali jadi miliknya.
Melihat adik iparnya yang culas, akhirnya Puyang Rie Tabing membuat batas. Dibuatnyalah tanggam sebagai penanda batas kebunnya dengan kebun adiknya tersebut”. kata Nenek Kam kembali.
“Akhirnya bagaimana, Nek? Apakah mereka bertempur mengadu ilmu kekuatan sebelum membuat batas tersebut?”Tanyaku.
“Iya, Puyang Rie Tabing memanggil adik iparnya lalu mengingatkannya mulai saat ini, ada batas antara kebun miliknya dan milik Puyang Serunting Sakti. Lalu, jika anak cucu keturunan Puyang Serunting Sakti, beliau larang dan tidak akan sanggup mendaki dan memasuki wilayah kebun Puyang Rie Tabing sampai sepanjang bukit Keraton. Hingga sekarang, anak cucu keturunan Puyang Serunting Sakti tidak akan pernah bisa naik ke bukit itu. Jika mereka masih nekat hendak mendaki, maka berbagai macam penglihatan akan mereka temukan. Akar berubah jadi ular, pohon dan daun jadi lipan, atau turun hujan lebat tidak berhenti-henti sebelum anak cucu keturunannya turun dan pulang” Lanjut Nenek Kam lagi.
“Lalu apa hubungannya cerita nenek dengan wajah murung Nenek barusan?” Tanyaku. Sekilas Nenek Kam menatapku.
“Bukit itu menyimpan Kenangan tersendiri buat nenek. Dulu, ketika kakekmu tidak menyetujui Nenek untuk dekat dengan nenek gunung, Nenek sering dibawa Macan Kumbang ke sana. Berkumpul dengan nenek gunung-nenek gunung di Bukit Barisan ini” Ujarnya sambil sedikit tersenyum. Sejenak aku tercenung mendengarkan ceritanya.
“Waktu itu nenek berusia berapa tahun?” Tanyaku lagi. Lama Nenek Kam berpikir. Aku hanya mengharapkan kira-kira saja. Sebab bukan suatu hal yang mustahil orang zaman dulu tidak ingat tanggal kelahirnya. Ternyata terkaanku benar. Nenek Kam mendongak ke atas, dengan pandangan menerawang mengingat sesuatu.
“Waktu itu, kira-kira Wakmu Kamseri baru bisa berjalan sepincang dua pincang, sampai dia bisa main sendiri” Jawab Nenek Kam. Aku tersenyum dalam hati. Sepincang dua pincang itu maksudnya baru bisa melangkah satu-satu. Artinya ketika itu Wak Kamseri berusia sekitar satu tahun atau setahun setengah. Sampai Wak Kamseri bisa main sendiri, kemungkinan sampai usia tiga tahun.
“Nek, mengapa orang zaman dulu tidak pernah mencatat tanggal kelahiran anaknya?” Tanyaku. Sebenarnya pertanyaan berulang. Dulu juga sudah dijelaskan Bapak mengapa orang zaman dulu tanggal kelahiran hanya pakai perkiraan.
“Bagaimana mau mencatat rata-rata orang zaman dulu buta huruf. Tidak boleh sekolah oleh orang tua. Sebab kalau pintar nanti diculik Belanda. Kalau pun ada yang bisa membaca, paling mereka tulis di dinding pakai arang atau kapur tulis. Apalagi perempuan zaman dulu. Dilarang sekolah sama sekali. Ibumu saja hanya sebatas kelas empat Sekolah Rakyat. Untung ibumu cerdas. Meski hanya sebatas kelas empat Sekolah Rakyat tapi otaknya sama dengan sarjana sekarang” Lanjut Nenek Kam lagi. Aku senyum-senyum sendiri Nenek Kam sudah bisa membandingkan antara sarjana dengan tamatan Sekolah Rakyat setara SD zaman dulu. Selanjutnya aku kembali bertanya perihal menghilang Nenek Kam. Setahuku cerita Ibu dan kakek haji Yasir, Nenek Kam pernah hilang sepekan lamanya. Lalu kata Nenek Kam, dia pergi ke mana-mana. Kadang duduk-duduk di bawah rumah bersama nenek gunung. Beliau melihat kesibukan penduduk turun naik siang malam bergantian menjaga rumah dan pergi ke hutan dan bukit mencari jejak Nenek Kam.
“Dulu, Nenek tinggalkan dusun kita, lalu Nenek sengaja menghilang. Nenek jalan-jalan dari dusun satu ke dusun lainnya. Sesekali Nenek pulang melihat Kamseri, lalu pergi lagi. Entah berapa dusun, manusianya dikerahkan oleh Kekek Haji Yasir untuk mencari Nenek. Waktu itu Kakek Haji Yasir menjabat Rie. Masyarakat bergotong-royong mencari Nenek pada waktu itu. Padahal Nenek melihat semua aktivitas mereka” Nenek Kam bercerita sembari terkekek-kekek. Aku ikut tertawa. Sudah bisa kubayangkan suasana saat itu. Ketika kutanya mengapa nenek Kam tidak menetap di gunung Dempu? Beliau jawab kadang ke gunung Dempu, kadang di Bukit Selepah, Bukit Patahan, Bukit Pailan Ayam, Marcawang, Bukit Kayu Manis dan lain-lain. Akhir cerita Nenek Kam, setelah berminggu-minggu orang mencarinya tidak juga menemukannya, terakhir kakek suaminya dipaksa Kakek Haji Yasir untuk membawa sedekahan di pinggir dusun, sembari berbicara, “Relingin baleklah, aku tidak akan menghalangi takdirmu untuk menjadi manusia damai” Dengan perasaan galau kakek menuju pinggir dusun sendiri. Pasalnya beliau takut bersua dengan nenek gunung. Benar saja, di pinggir dusun ada tiga sosok nenek gunung sedang santai tidur-tiduran di bawah pohon bacang tua yang rimbun. Padahal jika batin seseorang peka, dia bisa melihat di tengah-tengah sosok nenek gunung itu ada Nenek Kam sedang bercengkrama. Dalam hati hati aku geli sendiri. Ternyata Nenek Kam preman dari muda.
“Beberapa malam lagi, sebelum kau berangkat ke Pekanbaru, Puyang Bukit Selepah menghendaki kau ke sana, Dek” Lanjut Nenek Kam lagi. Aku menatapnya sejenak sebelum bertanya apakah aku akan diantar Nenek Kam atau tidak.
“Kau bukan anak kecil lagi yang harus dikawal, Dek. Berangkat sendiri” Lanjut Nenek Kam lagi langsung menjawab pertanyaan batinkuku. Aku mengangkat alis pertanda tidak mendapat sambutan baik dari Nenek Kam. Dalam hati aku membatin, meski tidak berbarengan denganku, pasti Nenek Kam akan hadir di sana. Kalau tidak duluan, setelah terakhir pasti akan muncul wajahnya.
Sejenak kami berdua diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Dari atas garang pondok aku melihat dahan kopi bergoyang-goyang pertanda ada orang yang menyibaknya. Lama mataku mengawasinya untuk memastikan sosok siapa yang lewat.
Matahari belum terlalu tinggi. Kabut dan embun masih membasahi lidah daun. Ceracau burung kutilang, kepakkan sayap dan jeritan pipit masih riuh mengisi udara pagi hingga terdengar sampai ke lembah. Di kejauhan daun bacang yang masih muda, nampak seperti hamparan bunga berwarna ungu tua. Segar dan indah.
Tak berapa lama, sosok Kakek Haji Yasir menyembul dari balik rimbun daun kopi. Nafasnya terlihat sedikit terengah setelah berjalan dari dataran agak rendah.
“Relingin, siapa yang membersihkan ujung kebun? Kawan-kawanmu ya?” Kakek Haji Yasir sedikit mendongak. Kulihat Nenek Kam biasa-biasa saja.
“Ada apa Kak Haji? Alhamdulilah kalau sudah bersih. Lumayan kan ngurangin tenaga” Kata Nenek Kam sambil mengoyak beberapa lembar daun sirih. Kakek Haji Yasir manggut-manggut. Menurut beliau ketika berjalan ke ujung kebun, beliau melihat rumput yang baru ‘disiangi’ masih nampak sangat baru. Aromanya masih sangat segar dan belum ada yang layu. Artinya, rumput-rumput itu baru saja ditebas. Sementara kakek Haji Yasir tidak melihat orang bekerja di sana.
“Untung aku tidak bertemu dengan kawan-kawanmu itu” Ujar Kakek Haji Yasir sambil menyekah tanah lembab yang melekat di telapak kakinya. Kulihat nenek Kam tersenyum kecil. Dalam hati aku berpikir, akan berubah lain jika yang melihat hal ajaib itu ibu. Bisa dipastikan beliau tidak mau lagi datang ke ujung kebun.
Ketika kakek haji naik pondok, melanjutkan minum kopinya bersama Nenek Kam, aku turun lalu segera berjalan menuju tempat yang dimaksud Kakek Haji Yasir. Sementara ibu masih sibuk membantu Bapak mengeluarkan gelondongan kopi yang rencananya akan digiling hari ini. Sesampai di hilir, benar sekali. Aku melihat kebun bersih tanpa rumput. Dan rumput-rumput yang baru disiangi ini terlihat masih sangat segar. Tapi aku sudah tidak mencium aroma nenek gunung di sini. Padahal aku ingin tahu siapa saja yang disuruh Nenek Kam membersihkan kebun kakek Haji Yasir.
Aku terus. berjalan hingga ke sisi kebun. Di ujung kebun ada rawa-rawa. Konon kata Kakek Haji rawa-rawa itu dulu adalah paok, tempat nenek moyangnya memelihara ikan dan liling. Aku hanya melihat telur-telur kembuai yang berwarna orien melekat di tunggul-tunggul dan kayu mati. Entah berapa hari lagi, telur-telur kembuai sejenis keong berukuran besar itu menetas. Dulu ketika aku kecil telur-terur seperti kristal itu kerap kali kumainkan. Kuambil dan kulepas paksa di tunggul-tunggul, lalu seenaknya kupencet sehingga mengeluarkan bunyi berderai-derai seperti kaca pacah. Padahal, kalau ibu memasak kembuai aku paling suka. Dagingnya yang kenyal bahkan seperti karet tetap nikmat untuk dimakan.
Lama aku berdiri di sisi rawa. Beberapa anak sepat dan betok kulihat berenang pelan di air yang kecil. Dasar rawa terlihat kuning. Bahkan beberapa genangan air seperti berminyak. Kata orang kampung cairan seperti berminyak dan berkarat itu “tai ketam”. Mengapa disebut ‘tai ketam’ aku sendiri tidak tahu. Padahal ketam itu kepiting. Apa mungkin kotoran kepiting yang membuat air seperti berkarat dan berminyak-minyak?
Beberapa ekor burung berparuh panjang terlihat lalu lalang. Suaranya yang ramai membuat burung kicau berwarna kuning ini kerap pula dijerat oleh manusia. Aku memperkirakan burung kecil itu bersarang di semak-semak rawa. Rawa-rawa ini memang tempat yang aman untuk mereka berkembang biak dan terhindar dari gangguan anak manusia. Yang paling membahayakan telur dan anaknya adalah ular-ular pemangsa yang sering pindah dari pohon satu ke pohon lainnya.
“Dimana kau Dek” Suara Nenek Kam terdengar halus sekali. Nampak beliau menungguku hendak mengajak ke kebunnya. Aku langsung menjawab akan segera pulang. Padahal sebelumnya aku hendak menyisir pinggir kebun kalau singgah untuk melihat pohon ghukam yang tumbuh di tepi sungai kecil yang membelah kebun. Aku rindu dengan masa lalu berjalan mengikuti nenek Kam tengah malam bersama beberapa sosok nenek gunung sekadar untuk mengambil buah ghukam yang sudah masak dan jatuh.
Sebenarnya aku ingin juga melihat pohon sali. Apakah ada buahnya atau tidak? Biasanya sali itu akan berbuah berbarengan dengan musim kopi. Namun demi mendengar panggilan Nenek Kam aku mempercepat lagkah menuju pondok kakek Haji Yasir. Dari kejauhan kulihat daun pisang semakin menjulang. Rupanya karena pohon dedap dan pokat tumbuh tinggi di sampingnya, membuat pohon pisang ikut tumbuh tinggi juga. Yang membuatku tertarik adalah banyak sekali pucuk daun pisang yang masih muda bergulung-gulung dan melengkung. Bisa dipastikan di dalamnya anak kelelawar sedang berlindung. Dia akan ke luar petang dan malam hari, mencari makanan buah-buahan di sekitar kebun dan bukit.
Baru saja aku membayangkan tubuh mungil kelelawar yang bersayap panjang seperti sirip, dan berkepala seperti tikus, berwarna hitam keabu-abuan, memiliki taring dan gigi yang kecil-kecil, tiba-tiba aku melihat di pohon dedap tubuh kelelawar yang berukuran sangat besar, tidak seperti kelelawar pada umumnya. Dengan tubuh tergantung dan mata seperti melotot padaku. Aku diam sejenak. Dia bukan makhluk biasa. Melihat ukuran dan aromanya, kelelawar raksasa ini adalah bangsa jin yang berbentuk kelelawar.
“Aku raja kelelawar, anak gadis! Dulu, ketika kau masih kecil, seringkali kau memainkan anak buahku hingga tak berdaya. Bahkan ada beberapa ekor mati” Ujarnya menjawab batinku. Aku kaget bukan main. Selintas aku mengingat masa kecilku.
“Tapi bukan kelelawar di sini yang kumainkan. Kelelawar di Pagaralam” Jawabku sambil tetap berpikir keras di mana saja aku pernah menangkap kelelawar lalu kumainkan.
“Sama saja Gadis, mau kelelawar di seberang Endikat atau pun yang di Pagaralam. Mereka adalah anak buahku” Jawabnya cepat. Akhirnya aku minta maaf atas ketidaktahuanku. Kuakui masa kecilku memang bandel dan tidak ada takutnya. Termasuk menangkap lintah yang mendekati rakitku ketika aku bersama keponakanku bermain di tebat yang ada di simpang Bandar. Lintah-lintah yang berusaha merambat ke kaki kami kutangkap lalu kucacah dengan parang tumpul. Karena alotnya, aku pukul berulang-ulang lintahnya. Aneh sekali memang waktu itu, lintah-lintah itu seperti dikomando ramai-ramai mendekati rakit kami. Alhasil kami kembali menepi naik darat setelah aku melihat raja lintah yang tubuhnya nyaris selebar telapak tangan bayi. Dia ingatkan aku waktu itu dengan ancaman akan menghisap darahku jika masih membunuh anak buahnya. Sejak itu aku kapok, tidak mau lagi membunuh makhluk sekecil apa pun.
Akhirnya aku berpaling dari raja kelelawar yang menampakkan diri itu. Untung dia tidak mengajak bertarung. Akhirnya kuketahui jika dia tinggal di belakang bukit Kayu Manis jauh di rimba yang jarang didatangi oleh manusia. Di sanalah kerajaan kelelawar bersemayam. Pantas ketika aku berada di bukit Patah aku melihat gerombolan kelelawar terbang dari balik bukit itu. Rupanya di sana kerajaannya.
Dadaku masih terasa berdegup-degup. Rasa bersalah membuat penyesalan di batin.Pantas saja ketika aku ikut Kakek Haji Yasir ke kebunnya di kaki gunung Dempu waktu dulu, aku menemukan anak kadal tidak mampu berjalan karena lemah. Lalu kupungut anak kadal itu, kuletakkan di atas batu yang berumput, dengan maksud menjemurnya. Karena kerap kali aku melihat kadal menggoyang-goyangkan kepala, ekornya, saat matahari mulai naik. Kata kakek kadal itu berjemur. Makanya aku biarkan anak kadal itu berjemur di atas batu. Malamnya aku bermimpi didatangi kakek tua. Beliau memberikan tiga ekor kadal, lalu berpesan bakarlah kadal itu sampai gosong, lalu giling sampai halus, tambahkan minyak kelapa, kemudian oleskan pada telapak tangan kakekmu yang sakit. Waktu itu telapak kakek Haji Yasir seperti eksim. Anehnya ketika aku terjaga, di telapakku ada tiga ekor kadal. Tanpa pikir panjang, aku segera melakukan pesan kakek dalam mimpiku itu. Setelah aku bakar seperti arang, lalu kutumbuk halus. Selanjutnya kutambahkan minyak kelapa, lalu aku poleskan ke tangan kakek Haji Yasir yang sakit. Padahal baru saja ditempelkan, kata kakek rasa gatal, panas, sakit sebelumnya tiba-tiba hilang. Kakek mentapku setengah tidak percaya waktu itu. Lalu kuceritakan darimana aku dapat resep obat itu.
“Semua makhluk di muka bumi ini, pada dasarnya pandai bersyukur. Kau ikhlas menolong anak kadal itu, dia bisa merasakan keilkhlasan itu, Cung. Makanya mereka balas ketulusanmu dengan dengan memberikan resep obat dan tidak masuk akal. Siapa yang menyangka jika kadal makhluk melata yang berkulit licin itu memiliki keistimewaan. Allah memang maha kaya” Ucap Kakek Haji Yasir penuh haru ketika itu. Sejak itu, kakek banyak memberitahu obat tradisional pada setiap orang yang kena penyakit kulit akut. Benarlah kata hadist, setiap penyakit yang diciptakan Allah pasti ada obatnya. Hanya saja kita manusia tidak semua mampu mengungkap rahasia alam itu dengan mudah.
Sesampainya di pondok aku langsung mendekati Nenek Kam. Beliau sedang menyuap nasi goreng yang dimasak ibu. Dari sinar matanya aku tahu jika hari ini Nenek Kam hendak mengajakku pergi ke kebunnya.
“Siap-siaplah. Sebentar lagi Macan Kumbang jemput kita” Ujarnya setengah berbisik. Aku mengangguk tanda mengiyakan. Meski dalam hati aku bingung, apa yang harus aku persiapan? Paling membawa baju selembar dua lembar untuk ganti.
“Bu, aku diajak nenek ke kebunnya, boleh kan?” Tanyaku dari atas beranda. Ibu hanya mengangguk sambil meletakkan karung-karung kopi yang telah kosong ke jemuran. Sebenarnya aku tahu, ibu tidak akan menolak. Apalagi melihat Nenek Kam perawakannya semakin ringkih.
Belum kering lidah nenek Kam menyebut sebentar lagi Macan Kumbang datang, tiba-tiba aku mendengar langkah beratnya. Benar saja. Setelah aku menoleh Macan Kumbang sudah berdiri di depan pintu. Si ganteng yang alim ini sebentar lagi akan jadi pengantin aku membatin. Matanya tajam menatapku. Tidak ada canda, apalagi tawa seperti biasanya.
Aku segera menghampirinya. Mata kami beradu. Aku mencoba menyelami perasaannya.
“Jangan usil! Mau tahu saja urusan orang” Ujarnya dengan nada marah. Aku mengangkat bahu sambil terus membaca perasaannya tanpa mempedulikan ketidaksukaannya. Ternyata Macan Kubang serius tidak mau diketahui perasaannya. Diam-diam dia halangi aku. Diam-diam kulawan pula, bahkan kuserang. Tak lama aku tertawa terpingkal-pingkal. Wajah keruh Macan Kumbang disebabkan karena cemburu. Rupanya dia cemburu dengan calon istrinya, Putri Bulan. Pasalnya, ada pemuda dari ranah Minang yang berusaha mendekatinya. Padahal pemuda itu sudah tahu jika Putri Bulan akan menikah. Pendek kata, pemuda itu seperti bertaruh, jika Putri Bulan akan menikah dengannya. Bukan dengan Macan Kumbang. Selanjutnya, Putri Bulan menemuinya baik-baik, lalu mengingatkan nya agar jangan mengusiknya. Apalagi pernikahannya tinggal menghitung hari. Ternyata, Macan Kumbang cemburu dan marah, karena dirinya dilarang menemui pemuda lancang itu. Padahal Macan Kumbang ingin menantangnya. Harga diri kelelakiannya diinjak-injak. Ini kali ke dua ada lelaki yang mengusik hubungannya.
Aku tahu perasaanMacan Kumbang. Bahkan aku juga ikut marah dengan pemuda itu. Aku bertekat akan membuat perhitungan dengannya. Macan Kumbang dan Putri Bulan tidak perlu tahu. Aku akan pakai caraku sendiri. Sekarang saatnya aku harus membuat Macan Kumbang tersenyum.
“Tuanku Macan Kumbang yang terhormat. Terimalah sembah sujud hamba. Maafkan kelancangan hamba karena mampu masuk dan membaca jiwa Tuan. Sekarang, hamba pasrah. Hukumlah hamba, Tuan” Ujarku duduk bersilah seperti menghadap seorang raja.
Tiba-tiba air muka Macan Kumbang berubah. Ternyata apa yang kulakukan berhasil. Wajahnya tidak tegang seperti tadi.
“Hukumlah hamba, Tuan. Hamba mengaku salah” Ujarku lagi. Kali ini kubuat ekspresiku sedikit memelas.
Creet!!
Aku kaget! Tangan Macan Kumbang cepat sekali menarik rambut dekat telingaku. Aku berusaha menahan sakit dengan posisi kepala miring.
“Adew…adew….adew” Aku menjerit. Aku berusaha pasrah. Kulihat Macam Kumbang tertawa.
“Ini hukuman buat yang lancang! Selanjutnya, kamu saya pecat!” Suara Macan Kumbang.
“Jangan tuan, kalau hamba dipecat, anak-anak hamba makan apa, Tuan. Ingin makan batu, keras Tuan. Ingin makan angin, bisa membuat perut kembung. Mohon ampun Tuan, jangan pecat hamba. Hamba masih lajang tuan, belum laku. Eh! Salah! Ralat! Tadi aku bilang dah punya anak. Kok malah mengaku lajang dan belum laku?” Ujarku terpingkal-pingkal. Karena memang lidahku keseleo. Macan Kumbang ikut tertawa lepas.
Aku tidak menyangka tingkah laku dan bahasa tubuhku diperhatikan ibu dari jauh. Air mukanya berubah-ubah. Terakhir melihat aku tertawa lucu sendiri membuat beliau makin heran. Berkali-kali tangannya mencuil-cuil tubuh Bapak agar Bapak ikut memperhatikan aku. Sesekali pula Bapak menoleh sembari tersenyum kecil. Sementara aku tidak bisa menahan lucu sendiri diikuti Macan Kumbang.
Kulihat aura Macan Kumbang berubah jernih tidak keruh seperti tadi. Aku memang sangat paham sifat adik bujang Nenek Kam satu ini. Melihat aku dan Macan Kumbang tertawa lepas, nenek Kam hanya senyum-senyum sambil berkemas.
Nenek Kam sudah duduk di punggung Macan Kumbang. Aku mengiring di belakangnya. Kami berjalan menuju kebun Nenek Kam. Setelah sampai di pondok Nenek Kam, aku pamit segera ke luar. Macan Kumbang baring-baring di samping Nenek Kam. Sebentar lagi pasti ada yang mengantarkan makanan, jadi aku tidak pusing harus menyalakan api dapur. Aku segera pergi ke arah bukit barisan perbatasan Bengkulu dan Sumbar. Aku akan menemui lelaki dari ranah Minang yang mengusik Macan Kumbang dan Putri Bulan. Aku akan buat perhitungan dengannya. Wajah dan tempatnya aku sudah tahu. Beliau penghuni lembah di tengah hutan belantara yang belum pernah tersentuh oleh bangsa manusia. Sambil menuju tempat tinggalnya aku sudah kontak batin sebelumnya. Beberapa kali aku ditertawakannya. Bahkan terlontar kata-kata tabu dari mulutnya.
“Keluarlah datuk! Aku tidak main-main. Aku datang ke mari untuk mengajarkan etika dan adab pada Datuk. Bila perlu mulut Datuk akan kucuci agar bersih. Jika tidak mau, akan kusumpal dengan tanah” Ujarku berteriak di atas jurang yang menghadap ke sungai. Sengaja kukerahkan kekuatan agar semua penghuni jurang gelap ini tahu ada sosok perempuan yang datang, dan perempuan itu datang dari jauh.
Tak lama aku melihat semua daun di hutan bergoyang. Persis seperti angin puyuh. Suara mendesau simpang siur seperti hendak mengangkat pohon dari akarnya. Aku sudah memperkirakan hal ini. Lembah ini bukan tempat yang aman bagi siapa pun. Bangsa demit yang sakti-sakti ada di sini. Mereka adalah petapa-petapa sakti yang datang dari mana-mana. Aroma anyir dari dasar jurang membuat perutku mual dan ingin muntah.
Sesaat aku diam memperhatikan pohon-pohon yang bergoyang. Aku konsentrasi mengawasi sekeliling. Beberapa sosok sudah hadir namun tidak berani mendekat. Mereka hanya menatapku dengan mata bersinar seperti bara dari jauh.
“Mana pemimpin kalian yang bermulut dan berotak busuk itu? Mengapa kalian tidak berani mendekat? Aku tidak butuh kalian. Aku butuh pemimpin kalian yang kemari” Teriakku. Namun tidak ada jawaban. Makhluk-makhluk itu malah menyebar seperti membentuk pagar betis. Mereka mengepungku.
“Hei pengecut!! Datuk!! Begini caranya kalian menyambut tamu? Menyuruh anak buahmu mengepungku lebih dulu. Pemimpin apa dirimu, Tuk?” Ujarku masih berdiri di bibir jurang. Aku sudah memperkirakan akan mendapat sambutan seperti ini. Makhluk seperti ini tidak hanya jahat, tapi juga licik dalam menjebak lawan. Aku berusaha sabar menunggu kehadiran Datuk yang belum kuketahui namanya itu. Aku hanya tahu, sebenarnya dia adalah lelaki tua renta yang mengubah wajahnya menjadi pemuda tampan, hendak mengacau rencana rumah tangga Macan Kubang dan Putri Bulan.
Tak lama, aku mendengar suara gemeruduk dan mencuing namun tidak tahu asalnya dari mana. Bibir jurang yang kuinjak bergoyang seperti bergerak. Belantara ini makin gelap. Hanya mata-mata merah saja nampak melotot seperti lampu melingkariku. Tak berapa lama, suara tawa Datuk aneh itu menggetarkan alam. Kekuatan energinya luar biasa. Aku sudah menutup beberapa panca inderaku sambil menunggu kehadiran Datuk sakti itu.
“Hebat sekali nyalihmu Piak. Apa kamu tidak takut kusekap di sini menggantikan Putri Bulan yang lembut dan cantik itu?” Suaranya berat menyapaku dengan panggilan ‘Piak’ dari kata Upiak, yang berarti gadis. Aku tahu, apa yang beliau sebutkan bukan gertak sambal. Ketika dia sudah berani menggoda Putri Bulan, artinya dia sudah siap perang. Sebelum hal itu terjadi, dan mereka diserang atau menyerang kerajaan gunung Bungkuk, aku yang akan menghalanginya lebih dulu. Aku tidak ingin ada korban dari kerajaan Gunung Bungkuk atau dari Besemah.
“Untuk menghadapi aku seorang saja, Datuk sudah menyiapkan pasukan dan berusaha memagariku. Yakinlah aku jika aku berhadapan dengan lelaki tua bangka dan pengecut! Menghadapi seorang perempuan saja mengirimkan pasukan yang tidak jelas. Aku kemari mendatangi sarangmu, tentu karena aku punya nyalih. Aku tidak ingkar dengan ucapanku. Aku kemari hendak mencuci mulutmu yang kotor itu atau menyumpalnya dengan tanah!” Suaraku sengaja kubuat lantang hingga mengimbangi getaran tawanya yang berenergi itu. Datuk misterius itu kembali terbahak. Namum masih belum mewujudkan diri.
Mendengar tawanya yang keras, aku tidak mau terpancing. Akhirnya kuimbangi tawanya yang menggelegar dengan tawa pula. Kami saling serang dengan energi tawa. Beberapa batu di bibir jurang runtuh. Demikian juga beberapa pohon besar yang menguntai di jurang. Sembari tertawa, kukerahkan kekuatan semua pohon yang ada di sekitar belantara ikut tetawa dan bergoyang-goyang sambil terus mengamati dimana posisi Datuk misterius itu.
Kulihat pasukan yang bermata merah mulai limbung dan sebagian lagi selonjotan tak mampu melawan energi kami yang beradu. Tawa kami sudah berubah menjadi senjata yang saling serang. Kekuatan pohon yang bergoyang dan tertawa kutingkatkan. Alhamdulillah semua bermata merah lenyap dari pandangan.
Setelah batinku menyisir semua sisi jurang, barulah kutemukan sebuah goa gaib dengan pintu sama persis dengan cadas tebing. Rupanya si Datuk masih berada di dalam goa gelap itu. Hebat sekali dia bisa mengerahkan kekuatan dari jarak jauh.
Sekarang aku berpikir bagaimana caranya mancingnya ke luar. Aku ingin berhadapan langsung dengannya.
“Datuk…Datuk, aku tahu dirimu masih di dalam goa gelap di sisi jurang. Kau takut berhadapan denganku rupanya. Baik, akan kuhancurkan goamu kalau kau tidak ke luar. Kuhitung sampai tiga!! Satu….dua…..ti…”
Duaaar!!!!
Bersambung…



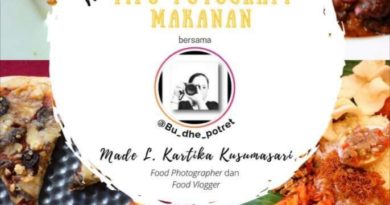

Alhamdulillah ada lanjutannya…
Sehat selalu ya buat adminnya… Amin
Salam rantau
Selamat malam dan salam sehat, maaf sedikit koreksi yaitu episode 99A dan 99B mestinya episode 98A dan 98 B… Terimakasih🙏
Terimakasih pembaca setia atas koreksinya.
Salam Diaspora
Admin